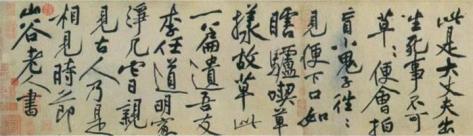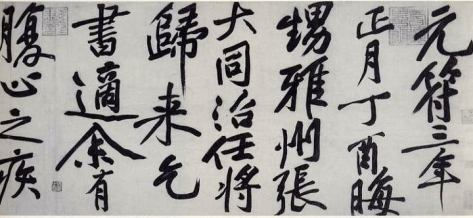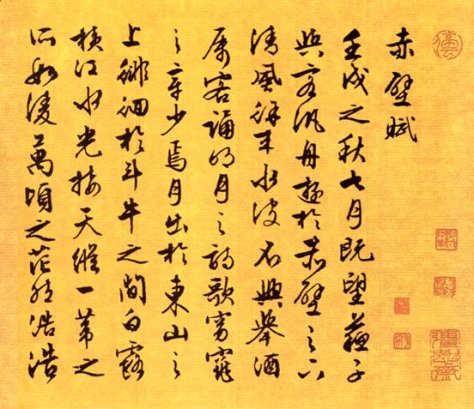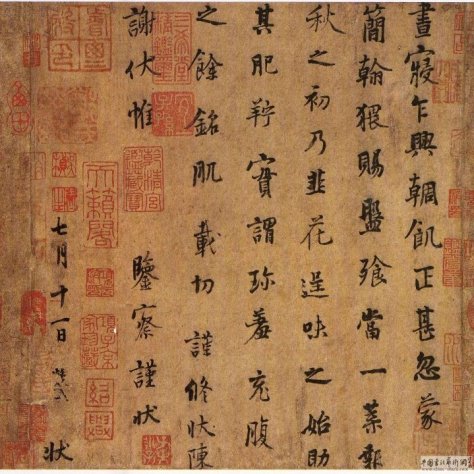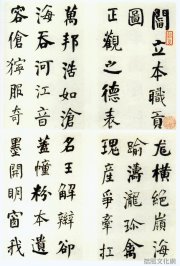Cerpen John Kuan
*
1

Di luar jendela adalah Central Park. Pepohonan yang gugur habis dedaunan di dalam musim dingin menjulur hingga jauh dari bawah telapak kaki, menampakkan semacam sapuan warna keabuan ranggas dan kuning keemasan, di dalam diam senyap mengisyaratkan daya hidup yang tak terhingga. Pencakar langit di sisi dua jalan besar sebelah timur dan barat taman berdempetan naik turun seolah bergerak pergi, menatap ke bawah hamparan pepohonan itu. Langit adalah abu-abu diselingi warna biru muda. Pukul delapan pagi, mungkin bertepatan dengan hari minggu, kau akan merasakan New York adalah mati kaku, seperti baru saja terjadi sebuah kudeta, diam-diam dirasuki sedikit gelisah dan teror, orang-orang berada di dalam rumah menunggu, mengamati, tidak tahu apa yang mesti dilakukan, tidak tahu bagaimana mengurus satu hari ini, waktu sehari penuh ini.
Dari lantai enam belas memandang ke bawah, jalanan seakan kosong luas terbentang. Lampu lalu lintas masih berkedip seperti biasa. Di seberang jalan ada dua patung perunggu, dua-duanya adalah penunggang, dengan gaya pamer perkasa pamer wibawa, menebarkan hijau murung yang kuno, topi tentara dan tapak kuda membentuk sudut yang agak menggelikan, keseimbangan yang tak terkira. Pedang panjang penunggang menunjuk ke bawah, saya konsentrasi memandang ke arah itu, di bawah ujung pedang yang tajam ada dua lelaki mengelilingi sebuah drum sambil berloncat, di dalam drum dihidupkan segumpal api yang penuh asap, mungkin koran kemarin, dipungut dari tong sampah. Mereka menyulut koran dengan api, lalu berdiri di sisi drum mengambil kehangatan, mengerutkan leher menggosok telapak tangan, sesekali meloncat, juga berbicara, namun saya tidak dapat mendengar apa yang mereka ceritakan. Api berkobar sejenak kemudian melemah, mereka bergilir pergi mengorek ke dalam tong sampah yang di sisi jalan, setumpuk-setumpuk koran dilempar ke dalam drum, asap putih tiba-tiba memanjat naik, di pagi yang dingin beku, di satu pojok taman, di bawah ujung pedang patung penunggang perunggu.
Merpati-merpati yang bangun pagi berpencar terbang datang.
Merpati-merpati lalu mendarat di lapangan, senyap sekali.
2.
Saya menarik sebuah kursi ke mulut jendela, duduk menguji kesunyian. Beberapa orang di kamar lain sedang berbicara tentang masalah kebebasan berpendapat. Sesungguhnya tidak ada yang perlu dibicarakan, sebab mereka saling menyetujui, hampir sepenuhnya saling menyetujui, kebebasan berpendapat adalah hak asasi, semuanya seperti berebut mengatakan, samasekali tidak bisa diubah dan sebagainya dan sebagainya. Mereka seperti bukan sedang bertukar pendapat, tetapi lebih mirip bertukar logat masing-masing. Sesekali terdengar ada suara mengaung: Chauvinism!
Sekarang di atas jalan yang membelah taman mulai ada beberapa mobil bergerak pelan-pelan, keluar masuk di antara pepohonan. Langit menampakkan sekeping biru, cahaya matahari dengan hangat menyorotinya. Di telingaku terdengar gaung suara orang-orang berbicara, tanpa henti, penuh diselingi suara gelas berbenturan dengan es batu, dan suara batuk yang sesekali melayang naik. Semua ini mengapung di dalam ruangan, cahaya lampu memenuhi hingga ke setiap sudut, dan di luar jendela adalah diam senyap.
Mereka bergiliran mengeluarkan pendapat, sepenuhnya saling menyetujui.
3.
Sore itu saya kembali ke mulut jendela melihat Central Park, pepohonan, dan pencakar langit yang berkilau di dua sisi. Hari itu sejak pagi, matahari masih belum mengundurkan diri. Di jalanan kian bertambah pejalan kaki, bahkan ada beberapa pedagang sedang menjual sweeter di mulut pintu taman, sehelai-sehelai digantung di minibus, berwarna terang, membuat orang berhalusinasi musim semi telah tiba.
Tapi musim semi belum tiba, atau mungkin sudah tiba. Saya melihat danau kecil berbentuk bulan sabit di dalam taman, setelah lama membeku, ternyata mengepak beterbangan beberapa ekor merpati yang riang. Merpati bermain air di beberapa bagian permukaan danau yang sudah mencair, bolak-balik menjulang menusuk, begitu mendekati permukaan air mengepak sayap mereka, cepat dan bernyali, menebarkan percikan air yang tak terhitung, begitu semangat bergiliran mengepak sayap, berebutan, tidak juga takut air danau yang baru mencair terlalu dingin.
Saya berdiri di tempat tinggi. Seumur hidup ini masih belum pernah melihat pemandangan yang begitu nyata, mencairnya sedanau air, setelah air danau itu menutup diri karena terlalu lama menahan dingin, setelah terkejut jadi retak-retak, tiba-tiba karena ada aliran hangat lewat, ternyata bisa juga dengan diam-diam mencair dari dalam, bahkan meluap keluar segenang air jernih, sekalipun di saat orang-orang bergegas memburu perjalanan, atau agak bosan terpaksa berdagang keliling sweeter, atau mengurung di satu sudut lantai tinggi berdiskusi Whitman, berdiskusi sastra anak-anak, memetik, meminjam, menghempas dengan keras sebuah ungkapan, mengisap rokok dengan gelisah, agak panik menggunakan Bahasa Inggris, sedang menguji-coba perlunya perdebatan dan unjuk diri, satu musim semi tiruan seakan telah tiba, air danau telah mencair, merpati dari tengah jalan terbang masuk ke dalam taman, sedang membersihkan sayap mereka di permukaan air yang dangkal.
Di bawah cahaya matahari musim dingin yang hangat dan warna-warni, merpati mengepakan sayap mereka dalam tempo cepat, gayanya yang bernyali itu bahkan membuat orang lupa bahwa sesungguhnya mereka mesti termasuk salah satu jenis burung berwarna abu-abu, sekarang tanpa henti memamerkan bulu-bulu mereka yang putih bersih, yang tersembunyi di tempat yang paling mendekati darah dan tulang, pernah di dalam dingin beku mempertahankan sedikit kehangatan. Saya dari atas menatap ke bawah, seolah mendengar sepotong alunan piano yang jernih, jari-jari tangan lentik bergerak berloncat dengan cepat beterbangan di atas tuts-tuts hitam dan putih, hanya melihat kumpulan merpati mendekati permukaan danau berputar, menusuk ke arah air jernih yang baru mencair, mengepak dengan sayap-sayap bergelora, menebarkan percikan air yang menyilaukan mata, berpijar bagai api.
*
See, they return; ah, see the tentative
Movement, and the slow feet,
The trouble in the pace and the uncertain
Wavering!
——— Ezra Pound
1.
Saya ingin berbicara denganmu, dengan cara begini. Saya ingin duduk begini, duduk di mulut jendela, di luar hujan masih terus turun, seolah belum pernah berhenti sejak tadi malam. Di luar jendela kamar penginapan, langit dan bumi basah kuyup, dinding-dinding gedung tampak berwarna kuning pupus, jejak-jejak air malang melintang tercetak di atasnya, bergetar di dalam lembab dan dingin. Di satu sudut yang agak jauh tegak sebatang tiang bendera yang luar biasa besar, bendera yang terlalu lama direndam air hujan, menumpuk jadi segumpal kain basah dan berat, walaupun warnanya tampak jelas, tetapi lelah tergantung di sana, samasekali hilang semangat. Lebih jauh lagi apapun sudah tidak kelihatan, bersembunyi di belakang hujan senja, ada sedikit bayangan agak kabur, mungkin atap restoran, atau papan reklame, atau antena. Saya sesuka hati menyapu pemandangan di luar, ada semacam perasaan yang aneh: Bagaimana bisa bertemu dengan cuaca yang begini lembab, di Taipei?
Saya coba mengatur kembali pikiran yang kacau.
Hanya kacau saja, tidak apa-apa, bukan, bukan, bukan tidak senang, bukan gelisah.
Saya sudah lupa kapan pertama kali berkunjung ke kota ini, lima belas tahun yang lalu? Atau lebih? Musim panas tahun itu saya seorang diri datang ke kota ini. Kita berjanji bertemu di sebuah kedai kopi, seperti biasa, cerita-ceritamu membuat seluruh perjalanan menjadi ringan. Saya mesti mundur lagi lima tahun, teringat malam pertama kita, di atas sepuluh ribu kaki, membelah Lautan Teduh, saya ingin mengajak kau bicara, bersama-sama membunuh waktu yang tak terhingga di dalam sebuah penerbangan panjang, namun kau mati-matian menggenggam sebuah injil, membenamkan diri ke dalam cerita-cerita kudus, saya tidak tahu harus masuk dari celah sebelah mana. Akhirnya saya mengambil resiko dengan beberapa buah puisi, sebotol tabasco dan sesungai cerita ikan salmon melawan arus mempertahankan spesiesnya. Ternyata ampuh, kau mencair jadi searus air jernih, sebuah nyanyian merdu dari lembah yang hening, tanpa henti, dari Taipei hingga Anchorage hingga Seattle hingga New York, saya disihir jadi pendengar tak terhingga, dan kau tetap adalah gadis dari sekolah katolik yang ingin menjadi santa.
Kau membawa saya keluar masuk lorong-lorong sempit, bercerita tentang rencanamu pindah ke San Fransisco, membeli sebuah rumah di tepi laut. Kita berputar dan berputar lalu keluar di sebuah jalan yang cukup lebar, saya masih pendengar tak terhingga, tetapi di saat matahari senja dengan potongan-potongan besar cahayanya menumpah di atas bangunan di satu sisi jalan hingga terang dan mewah, konsentrasiku pecah, sedikit tersentuh melihat bangunan itu berkata:
” Matahari ini sungguh bagus ”
” Memang bagus. Begitu terang. Begitu hangat. ”
” San Fransisco pasti juga begitu. ” Saya berkata: ” Sesungguhnya belum pasti. Ada orang merasa California semestinya begini atau begitu, namun sering bukan demikian. Nathanael West pernah menulis sebuah novel… ”
” Novel apa? ”
” Judulnya sudah lupa. Begini kira-kira ceritanya, ada seseorang yang sejak kecil seluruh harapannya tertuju ke California. Dia tumbuh besar di sebuah kota kecil di Midwest. Dia berpikir, California sama dengan buah orange dan sinar matahari, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya dengan susah payah dia sampai di California — mungkin California Selatan — baru menyadari bahwa bukan di setiap tempat dapat menemui buah orange dan sinar matahari. Mungkin saja ada buah orange dan sinar matahari, namun juga ada hal-hal lain, seperti berbagai macam kekerasan, penipuan. Dia sangat kecewa. ”
” Lalu? ”
” Sangat kecewa, lelah, sedih. ”
” Lalu? ”
” Lalu mati. ”
” Mati? ”
” Mati. ”
Kau berkata bahwa saya benar-benar tidak pandai bercerita. ‘ Lalu mati ‘ bagaimana bisa dianggap sebagai penutup novel? Saat itu kita berputar masuk ke jalan lain, pelan-pelan bergerak ke depan menghadap matahari senja, seperti tak berujung, seperti menuju rumahmu yang di tepi laut, di San Fransisco itu. Kau kelihatan begitu bersemangat, mulai mendeskripsikan bagaimana dan bagaimana rumahmu yang di tepi laut itu. Saya kehilangan konsentrasi. Bukan tidak berminat, saya sangat nyaman memandang jalan yang terhampar di depan, cahaya matahari senja yang berpijar jatuh menutupi seluruh jalan, memantul di atas rumah-rumah bergaya kolonial, genteng merah, tembok putih, pagar rendah dan pohon hijau bunga merah. Kau terus mendeskripsikan rumahmu yang di tepi laut, saya hanya menyahutnya, tidak henti-hentinya mengangguk.
2.
Saya membawa sebuah payung hitam turun ke jalan, keluar masuk lorong-lorong, berputar dan berputar, tergesa-gesa menyeberang, saya ingin begini berbicara denganmu, dalam suara hujan, dalam suara nafas saat berjalan, mobil-mobil bergerak pelan dan senyap, samasekali tidak terdengar suara mesin. Air hujan yang jatuh di atas payung, menimbulkan suara tumpul yang menggema, membuat saya terasa begitu aman, benar-benar aman. Di atas trotoar bata merah orang lalu lalang, tidak kelihatan ada raut wajah tidak bahagia. Taipei telah hujan. Muka toko besar maupun kecil semuanya bergantungan butiran air dan uap, namun di dalamnya masih seperti biasa, banyak orang berdiri atau duduk, sedang memilih lagu-lagu di dalam cakram, sedang menutup dan membuka buku, sedang memperhatikan sebuah baju rajutan, sedang mencoba sebuah topi, sedang tertunduk menyeruput sup, sedang dengan sendok keramik menikmati pangsit rebus, ada orang angkat kepala minum anggur, matanya menatap lurus keluar jendela, tepat mengenai saya. Di sudut lobi sebelah sana, terpisah sebuah meja ada lelaki berbicara dengan perempuan, di dinding tergantung beberapa lembar poster, selembar adalah New York, selembar adalah Brussel, selembar adalah Sydney, selembar adalah Bali.
Saya samasekali tidak ada ekspresi tidak senang, sesungguhnya saya sangat senang, saya dan kau yang hidup di dalam nafasku, kita cukup tidur, kondisi prima, samasekali tidak ada masalah jetlag. Saya tertarik memperhatikan orang-orang yang berjalan di trotoar, berani pastikan yang menyeberang ke sana kemari sebagian besar adalah turis, turis semacam diriku, di musim dingin, karena suatu keperluan harus melakukan perjalanan, mungkin bisa menemui sedikit kesulitan, mungkin juga tidak, dan dengan santai sudah mendarat di Taipei.
3.
Di hari kedua hujan sudah berhenti, saya masih juga keluar masuk lorong-lorong, berputar dan berputar. Orang-orang telah mengatupkan payung pegang di tangan, agak ringan mengayunkan kaki, lihat sana lihat sini. Dari satu sudut jalan yang agak jauh meniup datang sedikit suara seruling atau alat tiup lain, orang-orang mengitari satu pojok itu, kelihatannya seperti turis, iya, turis yang mirip diriku dan dirimu ini. Saya menpercepat langkah, sebab musik itu menarikku. Seorang polisi muda dengan seragam biru berputar keluar dari samping lalu bergerak maju serentak bersamaku. Dia mungkin juga tertarik oleh musik itu, matanya menatap lurus ke pojok jalan yang ada kerumunan. Suara musik kian dekat, nada yang tidak asing, seperti nyanyian, sahutan, keluhan orang Indian, juga seperti nyanyian Spanyol, membawa sedikit irama religi abad pertengahan yang bertahan hingga hari ini, displin agama Katolik dan puasa agama Islam, seolah, atau mungkin, adalah penyatuan syair dan nada itu, semacam harapan dan permohonan yang berulang kali ditumpuk, bermaksud, bersabar, dengan irama cepat disiarkan kemari, menceritakan, seolah, atau mungkin saja, seolah menceritakan sepotong dan sepotong kisah yang hampir sama, yang terjadi di dataran tinggi, di dalam lebat hutan hujan, di dalam sungai besar yang menggemuruh, di padang datar dan bukit yang dekat laut berangin, seorang lelaki dan perempuan saling mencintai, ternak diam-diam memamah rumput, di atas dahan burung-burung bercericit, dua ekor elang berputar di langit biru, di dalam dusun lelaki sedang menimba air sumur, sedang memperbaiki tapal kuda, sedang memberi makan keledai, perempuan-perempuan duduk menjadi lingkaran, di bawah pohon rindang sedang mengupas kacang, rambut tebal dibiarkan jatuh di pundak, di belakang punggung, di dalam gelap menembus sedikit keemasan misterius.
*
Begitu masuk saya langsung terpukau dengan semua yang ada di luar jendela, merasa kapan saja buka mata memandang keluar, seperti bisa diduga, akan terjadi sesuatu, misalnya matahari pagi dan cahaya senja bagaimana timbul tenggelam, awan dan angin bagaimana berubah, warna pulau-pulau, jejak kapal melintas, bahkan mungkin saja dapat melihat kibasan ekor ikan hiu — konon perairan ini adalah tempat ikan hiu berkembang biak. Tempat ini di ketinggian lantai sembilan, seandainya memiliki cukup kesabaran, bisa saja memandang hingga sangat jauh. Awalnya memang demikian, terhadap penorama asing ini memiliki semacam pandangan yang polos, tulus, antusias, romantis, oleh sebab itu tidak henti-hentinya mengatur jarak pandang, semoga dapat melihatnya dengan sangat teliti, paling bagus adalah teliti namun tidak begitu jelas; semoga membiarkan ia memelihara sedikit misteri, sehingga saya bisa bertahan lebih lama mencarinya, karena tidak mengerti maka lebih ingin mencari, tentu saya tidak tahu apa yang dicari, atau kenapa pernah mencarinya, sekalipun antusias, romantis.
Hampir tengah hari, saya ingat adalah di saat matahari tengah hari sedang berpijar, saya berjalan ke arah mulut jendela yang di sisi pintu kaca menuju balkon, pasti kelihatan lelah dan serius, wajah yang baru keluar dari tumpukan buku kurang lebih mesti begitu, dan di dalam ruangan sunyi senyap. Saat itu, cahaya matahari yang dipantul masuk dari arah tenggara sudah mundur habis, namun di empat dinding masih berpijar kehangatan, mungkin ditebarkan oleh bayangan air berkilau di permukaan laut yang jauh. Saya melihat seekor elang.
Dia begitu nyata berdiri di sana, di atas pagar balkon, mungkin hanya sedepa di luar pintu kaca, membuat saya demikian terkesima memandangnya, lalu dengan lirikannya yang mempesona memandangku sebelah mata, seperti samasekali tidak mengacuhkan, elang memandang saya sekali lagi, matanya persis seperti mata barbar yang dinyanyikan Du Fu, tapi kepalanya berputar lalu berhenti menatap air laut yang berpijar, lama sekali, baru memutar kembali, tetapi pasti bukan demi melihatku, dia begitu kanan kiri berputar mengamati, saya pikir itu hanya semacam gaya angkuh bawaan, refleksi pundak dan leher, tegar, tegas, berwibawa. Saya menahan nafas melihatnya, dia berdiri di dalam cahaya matahari, di belakang pagar balkon yang berwarna hijau apel adalah biru air laut yang luas, dan langit yang tak terhingga, menampilkan sebuah latar yang amat misterius sekaligus sangat biasa, timbul tenggelam berjalin dengan alunan tipis musik yang seolah dekat seolah jauh. Saya melihat, mendengar semua ini.
Elang begitu saja berdiri di atas pagar balkon, memamerkan pada saya gaya indahnya yang lengedaris. Kepalanya kokoh, warnanya hijau keabuan membawa sedikit kuning gelap; kedua matanya bergerak sangat cepat, dan paruhnya yang melengkung seperti setiap saat dapat melumpuhkan ular dan kalajengking di padang tandus. Bulu-bulu di sayapnya berwarna terang, mengikuti corak kepala dan leher menjulur, menutup, setiap helai bulu mungkin saja telah diatur, disusun, tidak ada sedikit pun kekusutan, berlawanan, begitu teratur, begitu tenang, terpenjam istirahat, samasekali tidak menaruh perhatian terhadap antusias dan eksistensiku. Dengan cakarnya yang laksana besi bagai rantai erat-erat mencengkeram pagar balkon, lihat kanan lirik kiri.
Mungkin di dalam hati terbesit berbagai macam bentuk dan suara yang berbeda. Atau mungkin di satu dunia lain yang jauh, saya juga pernah bertemu dengannya, dengan antusias, kaget, dan satu ketulusan yang sama untuk mengingat dia selamanya, dan menangkapnya, tidak perlu jaring perangkap atau anak panah, gunakan puisi:
Dengan kedua tangan bengkok dia cengkeram tebing;
mendekati matahari di tanah yang agak sunyi,
selingkaran dunia biru mengitarinya, dia berdiriLaut penuh kerutan merayap di bawahnya;
dari sebaris dinding gunung, dia memandang,
lalu berguling jatuh, bagai halilintar membelah langit——— Alfred, Lord Tennyson
Elang seketika seperti terganggu, sejenak setelah saya membisikkan enam baris serpihan puisi Inggeris ini, menghadap sepuluh juta garis cahaya emas yang bergetar, dia benar-benar menggulingkan tubuh jatuh, membuka sayap, begitu ringan, merentangkan kedua sayapnya yang kokoh, menggores langit, pergi.