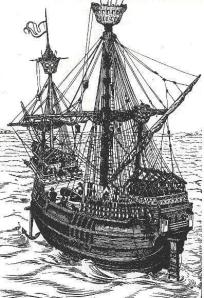Kolom John Kuan
Kadang-kadang tanpa sadar bisa mendapat tiga jam yang tak terduga, misalnya mengulang Dances with Wolves dari awal hingga akhir. Filem ini memberikan satu pandangan baru: Serigala adalah baik, kuda adalah baik, suku Indian ramah bersahabat, gagah berani, dan sangat bijaksana. Namun siapakah orang-orang jahat? Siapakah lemah, absurd, tolol, rakus, suka ribut, berkuda dan menembak dua-duanya tidak memadai, [buta huruf tambah tidak higiene]? Adalah perwira-perwira dan prajurit-prajurit kulit putih yang memakai seragam, adalah pasukan tentara utara yang menang dalam perang sipil, merekalah orang-orang jahat.
Ini adalah satu pengenalan atau kesadaran yang luar biasa. Kevin Costner telah mengubah ukuran tradisional filem western, seluruhnya dijungkir balik.
Seingat saya cuma ada satu yang pernah secara mendasar menelusuri masalah ini, dan dengan sepenuh daya membentangkan pandangan ini, yaitu [Legenda Ular Putih]. Di dalam legenda ini susunan tokoh baik dan jahat berturut-turut sebagai berikut: reptil, perempuan, lelaki, dan yang paling jahat ternyata adalah biksu. Ini sungguh adalah satu tambuhan genderang yang luar biasa! Cerita ini benar-benar secara total mengubah tolok ukur masyarakat tradisional Cina, seluruhnya dijungkir balik.
Demi serigala yang ditembak mati Tentara Federal dan meneteskan airmata. Demi ular yang dikejar dan dibasmi habis-habisan oleh Biksu Fahai dan meneteskan airmata, bahkan harus menambahkan satu bab [Pagoda Persembahan] sebagai poetic justice baru puas. Semua ini sungguh layak buat direnungkan.
~
Salah benar dan baik jahatnya seseorang, agaknya tidak ada hubungan dengan agama dan keyakinannya.
Agama dapat membuat seseorang tegar dan teguh, juga dapat membuat seseorang menyimpang dan keras kepala. Orang-orang yang percaya tuhan seringkali tidak takut mati, melihat singa datang menerkam, berdoa, tidak takut, ini adalah cerita penganut Agama Kristen pada masa awal, membuat bulu kuduk berdiri. Tentu, yang dimaksud [Tuhan], tidak mesti seperti yang ditentukan oleh ajaran Agama Kristen, bisa dengan berbagai cara memahami, menghayati.
~
Di dalam [Kompendium Lima Lampu – 五灯会元] dicatat kisah Guru Zen Yuande – 缘德禅师 dari Dinasti Song. Suatu kali Panglima Besar Cao Han sampai di Kuil Yuantong di Gunung Lu, Yuande duduk tenang tidak bangkit menyambutnya. Cao Han naik pitam: “Pak Tua tidak pernah mendengar Jenderal yang membunuh tak kedip mata?” Yuande buka mata menatapnya, agak lama baru berkata: “Kau tidak tahu ada biksu yang tidak takut hidup dan mati!”
~
Wang Shao (1030 – 1081) mengundurkan diri bertapa di Sungai Sembilan – 九江, Guru Zen Foyin (1032 – 1098) bersemadi di Gunung Lu – 庐山 , dan Wang Shao tetap masuk gunung memohon pencerahan. Foyin berkata kepadanya: “Tuan adalah Jenderal yang bersujud menyebut diri membunuh tak kedip mata, berdiri sudah jadi buddha, buat apa pencerahan?”
Kalau lihat catatan sejarah, Wang Shao adalah manusia yang sangat keji. Dia awalnya adalah pejabat sipil yang lolos Ujian Kerajaan. Di awal 1068 mempersembahkan [Strategi Meredakan Peperangan Perbatasan – 平戎策; baca: ping rong ce] kepada Kaisar Shenzong. Kaisar menerima strateginya dan mengutuskan dia memimpin pasukan menumpas Suku Qiang di daerah Sichuan. Penyerangan ini sangat berhasil, dan jabatannya pernah sampai tingkat menteri. Di awal 1081 meninggal dunia karena sakit. Orang ini sangat lihai dalam siasat perang, hanya saja sewaktu membunuh penduduk Suku Qiang yang menyerah, dia mencatat jasa prajuritnya dengan hitungan kepala yang terpenggal, luar biasa keji. Di masa tua kata dan laku tidak normal, sesat hati hilang akal. Tubuhnya hancur digerogoti bisul dan penyakit lain hingga seluruh organ dalam tampak, ada yang berkata karena sepanjang hidupnya membunuh terlalu banyak. Riwayatnya bisa ditelusuri di dalam Gulungan Nomor 321 Sejarah Song.
Foyin berkata [buat apa pencerahan], sesungguhnya sudah mengingatkan dia. Tetapi orang begini bagaimana bisa mengerti renungan Zen?
~
Pagi di kamar hotel lantai sepuluh, tirai sudah ditarik terbuka, cahaya lemah dan kelabu menembus masuk. Hujan seperti baru berhenti, rasa sejuk di luar seperti menyatu dengan suhu kamar yang dikendali pendingin udara. Ini adalah daerah Bugis di Singapura, berbagai bangunan baru dan lama menjulang berdempetan. Saya melihat tepat di luar jendela ada sebuah gereja.
Gereja ini mungkin dibangun pada abad ke-18. Saya ingat di dekat sana juga ada sebuah kuil Kwan Im dan sebuah kuil Hindu, walaupun sekarang tidak tampak di luar jendela. Itu adalah rute saya setiap pagi beberapa puluh tahun silam, setelah sembahyang di kuil Kwan Im pasti melewati pintu depan kuil Hindu, berhenti sejenak tukar senyum dengan penjaga kuil. Berjalan lagi beberapa saat akan bertemu dengan sebuah pintu besi yang selalu terkuak sedikit, di balik pintu adaah pekarangan gereja yang luas. Setelah menyusup ke dalam pekarangan, akan tampak di sana-sini bertebar beberapa batu nisan. Pintu gereja hampir selalu tertutup, saya belum pernah melihat bagian dalamnya, agaknya tidak akan jauh berbeda dengan gereja lain. Itu adalah jalan pintas saya menuju tempat kerja, bisa menghemat lima kali penyeberangan. Suatu kali saya membawa seorang teman melewati rute ini. Dia berkata: “Bagaimana kamu bisa menggunakan pekarangan gereja sebagai jalan pintas?” Saya melonggo. Mungkin karena pintu masuk dan pintu keluar selalu terbuka, jawabku. Tahun berikutnya saya mendapat kabar dia telah pindah ke Chicago belajar filsafat.
~
Gereja tua ini adalah bangunan paling pendek yang terpampang di depan mata. Saya bersandar di jendela memandang, hanya kelihatan dia berdiri berdempetan di antara begitu banyak hotel, bank, gedung perkantoran, dia kelihatan sedikit aneh. Dari tempat yang tinggi memandang sebuah gereja, terasa amat canggung. Dia merendah, khidmat, taat.
Begini dari atas memandang ke bawah sebuah gereja, seharusnya adalah jalur tuhan dan para malaikat, ini adalah semacam hak istimewa. Kita makhluk fana (tidak peduli pengikut atau tidak pengikut, saudara lelaki atau saudara perempuan) cocok dari bawah ke atas menengadah. Sebab sudah lama terbiasa, perlahan merasa cocok. Jika bukan kebetulan, bagaimana mungkin ada kesempatan yang aneh ini?
~
Bagian dinding luar gereja menempel sebentuk salib, tepat di luar jendela tempat saya berdiri. Salib ini kelihatan sangat berimbang, terkurung di dalam sebuah lingkaran, sebab itu atas bawah dan kanan kiri sama panjang, saling menyilang di pusat lingkaran, polos, sederhana, antik, sungguh merebut hati.
Setahu saya, salib begini disebut bentuk Yunani, mungkin ini adalah gereja Ortodok Yunani, namun teman pernah beritahu ini adalah gereja orang Portugis. Hal ruwet begini tentu bukan pencari jalan pintas seperti saya bisa menjelaskan. Saya juga tahu, salib yang paling sering kelihatan adalah atas bawah lebih panjang daripada kanan kiri, dan biasanya disilangkan di tempat yang agak tinggi, bentuknya seperti sebilah pedang menusuk ke bawah, disebut bentuk salib Latin Romawi Kuno. Seandainya di tempat persilangan salib Latin ada sebuah lingkaran, disebut bentuk salib Keltik, banyak ditemukan di Irlandia, Skotlandia, Wales, dan Inggris.
Panjang lebar di atas diperoleh dari ilmu lambang (heraldry).
~
Ilmu lambang ( heraldry ) tentu amat rumit, bukan saya bisa sepenuhnya memahami. Bentuk yang berhubungan dengan salib di dalam ilmu lambang (heraldry) sangat penting. Perbedaan antara bentuk Yunani dan bentuk Latin mudah sekali kelihatan. Dari dua bentuk ini berkembang keluar berbagai bentuk yang berubah menjadi warisan budaya yang sangat penting di dalam sejarah Eropa, di antara yang paling menarik selain yang dipasang di dalam dan di luar gereja, mungkin adalah yang tampak di bendera ksatria. Umpama salib Yunani yang sangat berimbang itu, jika di keempat ujung salib ditambah trefoil, disebut Botonee; jika di keempat ujung salib pecah bercabang dan agak melengkung ke dalam, disebut Moline.
Dengan salib Moline sebagai lambang bendera di era ksatria abad pertengahan Eropa, menunjukkan di dalam sebuah pasukan yang sedang menderu dan berkibas adalah putra ke-8 sang penguasa.
~
Di tengah kota Singapura yang sudah mirip dengan kota di dalam permainan komputer terdapat sebuah gereja tua, tentu bagus sekali. Di atapnya telah melekat banyak lumut, jendelanya yang jangkung dihias dengan kaca berwarna. Dindingnya agak tua dan kusam tetapi tampak masih kokoh, membuat hati terasa tenang dan damai. Di pekarangan samping yang cukup luas berhenti beberapa buah mobil.
Merpati.
Kembali lagi melihat merpati kepak sayap terjun dari atap gereja, tujuannya adalah pekarangan samping, mungkin di sana lebih mudah mencari makanan. Mereka bergegas mendarat, mengangguk, lalu kepak sayap naik, berputar-putar kemudian mendarat kembali.
Angin pagi bertiup perlahan, bersenda-gurau dengan merpati.
Beberapa bendera negara yang berbeda warna di ujung tiang yang tinggi, dengan sulit bergoyang, berlagak akan terbang, namun lesu dan lelah, seperti layang-layang yang tergantung di tiang listrik, tidak ada lagi harapan berkibas di angkasa.
~
Benda yang sama, dipandang dari atas ke bawah dengan dari bawah ke atas ternyata bisa demikian besar perbedaannya!
~
Saya sering teringat sebuah gereja gaya Spanyol di daerah pergunungan. Bangunannya tidak seberapa besar, tetapi pekarangan dan taman bunganya sangat luas, tentu dengan perbandingan yang sangat bagus. Saya juga sering teringat pastor yang bangun pagi di dalam taman, persis seperti babak II adegan 3 Romeo dan Juliet:
Mata kelabu pagi tersenyum pada malam tua berkerut,
awan satu per satu di timur berlumur cahaya,
langit hitam tembus berpijar bagai pemabuk
sempoyongan melintas di tempat roda langit membara.
Selagi matahari masih belum dengan matanya yang membakar
cemerlangkan hari menjemur kering embun malam yang lembab,
aku harus bergegas memetik lebih banyak bunga dan rumput unik
ingin mengisi penuh keranjang ranting dedalu kita
The gray-eyed morn smiles on the frowning night,
Checkering the eastern clouds with streaks of light,
And fleckled darkness like a drunkard reels
From forth day’s path and Titan’s fiery wheels.
Now, ere the sun advance his burning eye,
The day to cheer and night’s dank dew to dry,
I must upfill this osier cage of ours
With baleful weeds and precious-juicèd flowers.
Lalu dia selangkah sekata mengucapkan bentuk bebas sepuluh suku kata ini, dengan tenang berjalan melewati lorong, melangkah masuk ke dalam taman, sebuah taman beragam tumbuhan yang tidak terlalu lengkap.
Pemerintah daerah melakukan pelebaran jalan, ekskavator tanpa belas kasih mengeruk separuh pekarangan depan pastor, pagar didesak mendekati bangunan gereja, hanya menyisakan sepotong setapak tanah kuning yang sangat sempit.
Ah, keindahan yang maha kuat tiada batas berada
pada kandungan murni pepohonan, bunga, rumput dan batu
Oh, mickle is the powerful grace that lies
In herbs, plants, stones, and their true qualities.
~
Membangun sebuah gereja, di dunia Barat sering adalah memamerkan akumulasi perbuatan baik dari berbagai jaman, terutama membangun katedral. Dengan waktu seratus tahun dua ratus tahun, atau tiga ratus tahun putus-sambung menyelesaikan sebuah katedral, adalah hal yang sangat lumrah di abad pertengahan Eropa. Bahkan dengan tiga ratus tahun atau lima ratus tahun, atau lebih lama lagi, buat merasakan bahwa katedral tersebut masih belum selesai dibangun, juga merupakan hal yang sangat lumrah.
Katedral Koln yang di sisi Sungai Rhein, sudah dibangun beberapa ratus tahun, sampai sekarang masih belum selesai. Tentu, sekalipun katanya masih belum selesai dibangun, selama bertahun-tahun orang-orang juga terus menggunakannya, jadi sesungguhnya dia adalah bangunan lama yang sangat tua, namun masih belum selesai dibangun. Orang-orang jika memiliki kesempatan akan menambah beberapa potong bata, dengan tulus dan tegas, suatu hari akan serentak berkata: “Sudah, sudah selesai dibangun!” Jika membangun rumah dengan cara begini, harap jangan curi bahan lalai kerja, kalau tidak pasti dicaci maki anak cucu.
~
Konon pada masa-masa akhir Perang Dunia Kedua, pesawat-pesawat tempur Sekutu yang membombardir daerah-daerah yang dikuasai Nazi sangat berhasil, lalu masuk ke dalam teritori Jerman. Ketika ada pesawat tempur sedang bersiap-siap melepaskan bom di sekitar tepi Sungai Rhein, ada yang menyatakan, Katedral Koln tidak boleh dihancurkan. Markas besar Sekutu segera menurunkan perintah, pesawat pengebom harus menghindari Katedral Koln.
Maka katedral itu masih ada di sana, katedral yang belum selesai dibangun.
~
Dalam beberapa kali penyerangan terhadap Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat, pesawat-pesawat tempur Sekutu sering tanpa pandang bulu membombardir daerah aliran Sungai Tigris dan Eufrat yang disebut sebagai ayunan peradaban kuno itu, banyak sekali menelan korban, tentara maupun rakyat Irak — mereka seolah tidak mengangap orang-orang yang tinggal di sana manusia; kadangkala mengunci satu sasaran, menghancurkan semua bangunan yang tampak di atas bumi, sehingga fasilitas militer dan situs peninggalan kuno ikut celaka, hancur remuk — siapa peduli, juga bukan peninggalan peradaban Kristen, sekalipun pasti lebih tua beberapa ribu tahun dari katedral.
Ini adalah hal yang amat menyakitkan hati.
Seorang teman Kristen berkata pada saya: Di dalam injil ada nubuat, Babilonia yang jahat harus dihancurkan. ” Irak ” katanya: “adalah Babilonia yang jahat.”
Ini sungguh adalah sebuah alasan yang luar biasa.
~
Membangun katedral adalah semacam cara pengungkapan terima kasih kepada anugerah Tuhan. Seringkali, katedral juga pas digunakan sebagai tempat peletakan abu tulang tentara salib. Pada abad ke-13, menurut imajinasi David Macaulay, ketika orang-orang sepakat membangun sebuah katedral, mereka sudah siap dengan masa seratus tahun ke atas pelan-pelan menyelesaikan.
Tentu, seandainya berbagai syarat sudah terpenuhi, dan tidak ada peperangan, wabah penyakit, banjir dan kekeringan yang terlalu parah, dengan masa seratus tahun menyelesaikan sebuah katedral adalah sangat mungkin. Namun, manusia menghitung tuhan menentukan, peperangan dan bencana pada dasarnya adalah hal yang sering terjadi di dunia ini, dipastikan setiap saat bisa memutuskan perkembangan pembangunan, akan membuat kau keletihan, menderita, putus asa.
Seandainya bukan karena berterima kasih kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, pasti akan karena keletihan, menderita, putus asa lalu menyerah. Karena tujuan mulia begitu, maka tidak peduli betapa sulit juga akan dilampaui, hari ini tidak mampu besok lanjutkan, generasi ini mati masih ada generasi berikutnya.
Oleh sebab itu di dunia ini hanya ada katedral yang sudah selesai dibangun dan yang sedang dibangun, tidak ada katedral yang ditelantarkan tidak dibangun.
~
Tamu berkata: “Tentu ada, tentu ada yang ditelantarkan tidak dibangun.”
Saya terkejut bertanya: “Mana mungkin?”
Tamu berkata: “Seandainya orang-orang secara kolektif mengubah keyakinannya, atau tiba-tiba menemukan percaya tuhan atau kekuatan gaib adalah hal yang menggelikan, tidak lagi beragama, tentu rancangan katedral akan dibatalkan, tidak usah dibangun lagi.”
Saya berkata: “Eh, eh, bukan, bukan, atau ——— kau seharusnya berkata seandainya tuhan telah mati, maka tidak perlu lagi kita memeras otak mengagungkan Dia, begitu bukankah lebih gampang?”
Tamu berkata: “Dia? kata aneh apapula ini?”
Saya tersenyum menjawab: “Dia adalah dia,”
Tamu berkata: “Dia adalah dia! Ijinkan saya membaca sepenggal ini: [Dua orang itu balik badan meninggalkan tempat itu, menuju Sodom, Abraham masih berdiri di depan Yehowa. Abraham berjalan mendekat dan berkata: Tidak peduli orang benar atau fasik, Engkau juga akan memusnahkan? Bagaimana kalau di kota itu ada lima puluh orang benar, apakah Engkau akan memusnahkan kota itu juga, tidak demi lima puluh orang benar memaafkan orang-orang lain yang ada di dalamnya? Orang benar dan orang fasik dibunuh bersama, memperlakukan orang benar dan orang fasik sama, itu pasti bukan tindakan Engkau. Hakim segenap bumi, mana bisa tidak menjalankan keadilan? Yehowa berkata: Seandainya Aku menemukan lima puluh orang benar di Sodom, aku akan karena mereka mengampuni semua orang di tempat itu. Abraham berkata: Walaupun aku adalah debu, masih memberanikan diri berkata kepada Tuhan ——— seandainya lima puluh orang itu kurang lima orang, apakah Engkau akan karena kurang lima orang memusnahkan seluruh kota itu? Dia berkata: Seandainya Aku menemukan empat puluh lima orang di sana, juga tidak akan memusnahkan kota itu. Abraham berkata lagi kepadaNya: Bagaimana kalau ada empat puluh orang di sana? Dia berkata: Demi empat puluh orang itu, Aku tidak akan melakukan. Abraham berkata: Mohon Tuhan jangan marah, ijinkan aku berkata, seandainya di sana ada tiga puluh orang, bagaimana? Dia berkata: Jika di sana ada tiga puluh orang, Aku tidak akan lakukan juga. Abraham berkata: Aku masih memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau di sana ada dua puluh orang? Dia berkata: Demi dua puluh orang itu, Aku juga tidak memusnahkan kota itu. Abraham berkata: Mohon Tuhan jangan marah, aku berkata sekali lagi, seandainya di sana ada sepuluh orang? Dia berkata: Demi sepuluh orang ini, Aku juga tidak membinasakan kota itu. Yehowa setelah berkata pada Abraham lalu pergi, dan Abraham juga kembali ke tempat tinggalnya.]
~
Sodom hanya ada satu orang benar, namanya Lot. Menggunakan percakapan Abraham, kurang sembilan orang, kota ini pasti dimusnahkan. Malaikat memandu Lot sekeluarga ke Zoar, lalu Yehowa menjatuhkan belerang dan api di Sodom dan Gomora, [kota-kota itu, dan lembah Yordan, juga seluruh penduduk kota-kota itu serta yang tumbuh di atas bumi, dibinasakan.]