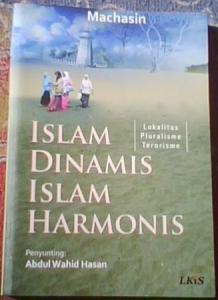Resensi Arif Saifudin Yudistira
Resensi Arif Saifudin Yudistira
Aku mencintai bahasa. Aku mencintainya karena perannya terhadap kehidupan kita, bagaimana bahasa menyediakan kita cara untuk mendedakan luka, keagungan nuansa dan kehalusan eksistensi kita (Maya Angelou)
Pram, begitulah kita mengenal sastrawan yang mencintai bahasa dan menggunakan bahasanya untuk berbuat. Pram barangkali adalah sastrawan yang tak hanya kritis tapi juga konsisten dengan apa yang disuarakan. Perjalanan karir dan hidupnya seperti lika-liku yang tak habis untuk dibaca. Di balik kebesaran dan nama Pram, kita mengenal sosok Pram yang lain, Pram dikenal sebagai sosok yang keras, tegas dan juga sangat kritis terhadap para pengkritiknya. Dunia sastra Indonesia seperti tak seimbang menempatkan posisi Pram di samping para sastrawan yang lain. Pram adalah luka, karena keberpihakannya pada PKI yang dinilai Pram sebagai partai paling konsisten terhadap revolusi. Pram pun mengalami nasib naasnya setelah peristiwa 65 dengan menanggung resiko karyanya dihanguskan dan dibuang di pulau buru. Tapi di sanalah Pram justru menciptakan kuartet pulau buru di tahun 1975 meski sudah dilisankan di tahun 1972.
 Karya-karyanya erat dengan kehidupannya, ia seperti meniupkan nyawa dalam karyanya, hingga karya itu secara tak sadar adalah suara jiwanya. Meski demikian, ia menganggap karya sastra tetap tidak bisa dikontrol oleh sang pencipta itu sendiri. Ia adalah anak dan buah pikiran dari penulis yang terbuka terhadap kritik dan interpretasi pembaca. Di awal kepengarangannya, ia kerap diserang oleh para kritikusnya yakni balfas desember 1956 novel perburuan dinilai tidak terstruktur, akhir kisahnya dibuat-buat dan tokoh-tokohnya tidak meyakinkan. Pram pun akhirnya naik pitam dan menanggapi dengan cara yang emosional. Kritik ini dilancarkan setelah Pram dan teman-temannya mempelopori gelanggang seniman merdeka tahun 1947. Tahun 1950 ia ikut menandatangani “surat kepertjayaan gelanggang” 18 Februari 1950. Pramudya ikut menyepakati konsepsi “humanisme universal” yakni istilah yang dipopulerkan oleh HB.Jassin yang menandai angkatan 45. Buku karya Savitri Scherer ini membantu kita memahami mengapa dan bagaimana Pramudya bisa ikut luruh dalam peristiwa perdebatan dan polemik sastra yang semula ia ikut dalam “gelanggang seniman merdeka” hingga akhirnya ia pun tidak sepakat dan melepaskan diri dari kelompok gelanggang, ketika ia bergabung dengan lekra, ia pun mulai simpatik terhadap PKI dan juga terlibat dalam polemik sastra yang menyerang para generasi baru gelanggang dalam manifes kebudayaan 1963.
Karya-karyanya erat dengan kehidupannya, ia seperti meniupkan nyawa dalam karyanya, hingga karya itu secara tak sadar adalah suara jiwanya. Meski demikian, ia menganggap karya sastra tetap tidak bisa dikontrol oleh sang pencipta itu sendiri. Ia adalah anak dan buah pikiran dari penulis yang terbuka terhadap kritik dan interpretasi pembaca. Di awal kepengarangannya, ia kerap diserang oleh para kritikusnya yakni balfas desember 1956 novel perburuan dinilai tidak terstruktur, akhir kisahnya dibuat-buat dan tokoh-tokohnya tidak meyakinkan. Pram pun akhirnya naik pitam dan menanggapi dengan cara yang emosional. Kritik ini dilancarkan setelah Pram dan teman-temannya mempelopori gelanggang seniman merdeka tahun 1947. Tahun 1950 ia ikut menandatangani “surat kepertjayaan gelanggang” 18 Februari 1950. Pramudya ikut menyepakati konsepsi “humanisme universal” yakni istilah yang dipopulerkan oleh HB.Jassin yang menandai angkatan 45. Buku karya Savitri Scherer ini membantu kita memahami mengapa dan bagaimana Pramudya bisa ikut luruh dalam peristiwa perdebatan dan polemik sastra yang semula ia ikut dalam “gelanggang seniman merdeka” hingga akhirnya ia pun tidak sepakat dan melepaskan diri dari kelompok gelanggang, ketika ia bergabung dengan lekra, ia pun mulai simpatik terhadap PKI dan juga terlibat dalam polemik sastra yang menyerang para generasi baru gelanggang dalam manifes kebudayaan 1963.
Goda Politik
Faktor-faktor yang menyebabkan Pram meninggalkan gelanggang dan akhirnya memutuskan hubungan dengan HB Jassin tidak semata persoalan politik semata, tapi juga karena Pramudya merasa dikhianati oleh prinsip-prinsip yang dinilainya tak sesuai dengan yang diajarkan Jassin kala ia mencetuskan “humanisme universal”. Pram menilai, Jassin dan para pengikutnya tak konsisten dan hanya “klenengan” dan tak mempedulikan rakyat sebagai aspek yang penting dalam karya sastra. Pram pun kecewa dengan sikap gurunya yang kemudian tak peduli ketika ia dipenjara karena menulis Hoa kiau di Indonesia (1960).
Buku ini mengurai dengan jelas mengapa Pramudya bergeser pada ideologi kiri dan memihak PKI. Meski ini berakibat dengan tuduhan ia adalah anggota PKI. Melalui lekra itulah ia bersuara dan menyuarakan prinsip-prinsipnya. Ia sadar betul, ide-ide awalnya bermula dari kritik para seniman dan kritikus lekra termasuk A.S Dharta yang membukakan matanya terhadap kenyataan-kenyataan sosial dan akan pentingnya arti rakyat dalam kesenian dan kesusasteraan. Ia pun tak mampu menahan goda politik yang waktu itu menjadi prinsip PKI bahwa politik adalah panglima, yang sebelumnya menggunakan demokrasi rakyat.
Melalui 10 bab dalam buku ini kita diajak tak hanya menelusuri karya Pramudya, riwayat kepenulisannya, tapi juga lika-liku politik dan kehidupan yang dijalani Pramudya sebagai penulis. Buku ini diawali dengan pendekatan kritis yang menganalisis terhadap perkembangan sastra Indonesia, kemudian menjelaskan kehidupan singkat Pramudya, bab berikutnya membahas tentang polemik sastra dan diikuti dengan pembahasan karya-karya Pramudya dan kontroversi karir Pram antara tahun 63-65. Menurut Savitri, Pramudya adalah penulis yang berdiri di tengah masyarakatnya dan bagian hakiki darinya, meminjam Teuw, Pram adalah “novelis yang tidak hanya mewakili Indonesia, melainkan juga seorang sastrawan yang mewakili kawasan Asia”.
Buku ini juga mendudukkan posisi Pram yang larut dalam posisi yang dilema antara berpihak pada corong partai atau tetap konsisten dengan karyanya yang dicipta. Ia menulis novel “Sekali Peristiwa di Banten” yang mencerminkan sikap Pramudya yang harmonis terhadap borjuasi nasional dan kekuatan angkatan bersenjata. Secara teoritis ini tidak sesuai dengan program pembentukan negara sipil sosialis. Di tahun 60, karya Pramudya yang membela minoritas tionghoa menyatakan siapa musuh Indonesia yang sebenarnya dan borjuasi nasional adalah bagian dari musuh tersebut. Savitri menyebut sikap ambivalen Ppramudya dapat dilihat cerminan akurat sikap ambivalen PKI terhadap “borjuasi nasional”.
Di akhir buku ini, Savitri menjelaskan bagaimana Pramudya menciptakan karyanya yang berbeda dari periode sebelum ia di pulau buru. Ia menciptakan “Bumi Manusia” dengan idealisme konservatif yang berbeda dengan “Gadis Pantai” dengan idealisme revolusioner. Bagaimanapun juga Pram adalah penulis yang tak pernah lepas dari prinsip-prinsip dan tujuan awal dia menulis yakni mendekapkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan tidak terlepas dari masyarakat. Pram adalah representasi dari sosok penulis yang konsisten dengan prinsip meski dengan sikapnya itu pula ia harus melibatkan diri dengan goda politik dan sikap politik partainya.
 Judul buku : PRAMOEDYA ANANTA TOER , Luruh Dalam Ideologi
Judul buku : PRAMOEDYA ANANTA TOER , Luruh Dalam Ideologi
Penulis : Savitri Scherer
Penerbit : Komunitas Bambu
Hal : 190 halaman
ISBN : 978-602-9402-02-5
Harga : Rp.50.000,00
*) Penulis adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Aktifis IMM, bergiat di Bilik Literasi Solo.